
Lorong Gelap | Cerpen : Ramli Lahaping
 Ilutrasi : detektif.jatim.com
Ilutrasi : detektif.jatim.com Detektifjatim.com – “Mari, Dik,” sapa lelaki paruh baya yang barangkali seumuran dengan almarhum ayahku itu.
Aku hanya mengangguk dan tersenyum menanggapi keramahannya.
Pagi ini, aku kembali melihat lelaki bergerobak itu lewat di depan rumahku, seperti yang kerap kusaksikan sebulan terakhir, setelah aku kembali menetap di kampung halamanku ini. Lelaki pemulung itu akan berkeliling menandangi setiap halaman rumah di dalam kawasan pemukimanku untuk mencari barang-barang buangan yang masih bernilai, entah plastik, kertas, besi, atau kaca.
Setiap kali melihatnya dengan semangat kerja yang tinggi, aku selalu merasa tersinggung. Aku yang masih muda, merasa tidak berguna. Aku yang lahir di tanah ini, lebih suka bermalas-malasan dan bergantung pada harta benda orang tua. Sebaliknya, ia yang seorang pendatang, seorang transmigran, malah memiliki kegigihan yang kuat untuk memajukan kehidupannya.
Kurasa, kenyataan itu juga disadari warga sedesaku. Kami yang lahir dan besar di kampung ini, bersantai-santai saja menjalani hidup. Di sisi lain, para pendatang dari pulau seberang begitu kreatif dan giat bekerja. Ada yang membuka warung makan, menjual gorengan, menjadi tukang servis elektronik, hingga menjadi pemulung atau pengumpul barang bekas.
Aku dan sebagian warga desa yang masih terhitung muda, memang tampak kalah tekun bekerja dibanding para pendatang. Kami lebih banyak menghabiskan waktu untuk berleha-leha dan bermain gadget. Bahkan kutaksir, ada beberapa orang di antara kami yang tampak lumpuh melakukan aktivitas positif karena kecanduan bermain gim judi daring dan terlibat penyalahgunaan narkotika, sehingga malah menjadi beban keuangan keluarga.
Tetapi mungkin, begitulah bentukan mental dalam kemasyarakatan. Orang kampung asli akan cenderung kalah maju ketimbang para pendatang. Pasalnya, orang kampung lebih menggantungkan hidup pada kemurahan lingkungannya, sedangkan orang pendatang lebih menggantungkan hidup pada perjuangannya sendiri.
Karena anggapan itu pula, aku pernah membuang diriku keluar kampung. Aku beranjak ke pulau seberang dan menetap di satu ibu kota provinsi. Aku kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan ekspedisi, sebagai kurir. Namun ternyata, hasil dari pekerjaanku itu tidak cukup untuk mengongkosi keperluanku. Dan masalahnya, bukan karena jumlah pendapatanku, tetapi karena kegemaranku yang boros dan penuh kesia-siaan.
Pergaulan yang salah memang telah menghancurkan hidupku. Bukannya menabung untuk masa depan, penghasilanku di kota seberang, malah kupakai untuk bermain judi, mabuk-mabukan, hingga mengkonsumsi obat-obat terlarang. Aku akhirnya jadi doyan sakau, hingga tabunganku benar-benar terkuras. Bahkan pendapatan sampinganku sebagai kurir narkoba, juga tak mampu menutupi ongkos kebadunganku tersebut. Aku lantas meminjam uang di sana-sini, hingga aku terlilit utang.
Demi lepas dari semua masalah itu, aku pun melarikan diri dengan pulang ke kampung halamanku ini. Dengan begitu, aku lepas dari penagihan orang-orang atas utangku, juga lepas dari pengaruh barang-barang terlarang.
Beruntung, ibuku masih menerimaku dengan baik. Ia rela menghidupiku dengan uang peninggalan ayahku yang dahulu hanya bekerja mengurus sepetak kebun jagung kami di kaki bukit. Tentu aku merahasiakan masalahku darinya dengan beralasan bahwa aku telah kecurian hingga tabungan hasil kerjaku selama tiga tahun, raib tak tersisa. Beruntung, ia percaya begitu saja.
Saat kehidupanku mulai beranjak dari titik minus ke titik nol, aku pun mulai memikir-mikirkan penghidupanku sendiri. Aku tak ingin selamanya berpangku tangan. Karena itu, aku mulai melupakan buaian-buaian kehidupan kota, kemudian mulai belajar mengurus kebun. Aku tak peduli lagi jenis pekerjaan yang akan kulakoni setelah melihat para pendatang begitu gigih melakukan pekerjaan receh yang halal, sebagaimana sang pemulung.
Di tengah renunganku perihal kehidupan, seorang pesepeda, penjual bubur kacang hijau, tampak di depan rumahku. Tiba-tiba, nafsu makanku bangkit. Berbekal sisa uang pemberian dari ibuku, aku pun menahannya dan membeli semanguk jajanannya. Aku kemudian melahapnya di teras depan rumahku, sembari mengamat-amati perubahan kehidupan desa selepas bertahun-tahun aku merantau.
Sekian lama berselang, santapanku pun tandas. Aku terus saja duduk sambil menikmati suasana pedesaan yang perlahan tertelan perkembangan teknologi. Hingga akhirnya, aku melihat lagi si pemulung berjalan di depan rumahku dengan gerobak yang setengahnya telah terisi barang pulungan. Karena merasa tertarik mengakrabinya, aku pun mengajaknya singgah dengan menawarinya botol plastik dan kertas bekasku.
Akhirnya, untuk pertama kalinya, aku berkenalan dan berbincang-bincang dengan pemulung itu. Dan sebagaimana tampakannya, ia adalah orang yang ramah dan nyaman diajak mengobrol. Dengan begitu saja, ia menceritakan tentang kehidupannya, hingga aku makin termotivasi untuk bangkit dengan penghidupan yang baru.
Sebaliknya, aku pun menceritakan perihal kehidupanku, sekadar untuk mengimbangi penuturannya.
Sampai akhirnya, setelah membincangkan banyak hal sembari bercanda, pemulung itu berseloroh, “Aku dengar-dengar, di sana, penyalahgunaan narkotika marak juga, ya? Apa kamu tidak berurusan dengan itu?” tanyanya, menyinggung kehidupanku di kota seberang.
Aku pun tergelak pendek. “Ya, kalau cuma coba-coba saja, pernah sih. Tetapi aku tidak sampai ketagihan,” kataku, setengah jujur.
Ia balas tertawa. “Ya. Baguslah kalau begitu.”
Aku tertawa saja.
Pembicaraan kami lantas menjeda. Si pemulung mendapatkan pesan singkat, sehingga ia fokus pada ponselnya.
Seorang pesepeda motor yang tampak sebagai penjual bakso, kemudian singgah di depan rumahku.
Beberapa saat berselang, aku dan sang pemulung kembali terlibat obrolan kecil yang terkesan sebagai percakapan penutup.
Lalu tiba-tiba, empat orang berpakajan biasa yang berboncengan dengan dua motor, datang dengan laju yang cepat dan berhenti di halaman depan rumahku. Dua orang di antaranya lantas menodongkan pistol ke arah aku dan si pemulung.
“Angkat tangan, dan jangan bergerak!” perintah seorang di antaranya. “Kami polisi.”
Kami menurut saja.
Diam-diam, aku jadi sangat khawatir. Aku takut kalau perkaraku di kota seberang adalah musababnya.
Tetapi akhirnya, aku bisa bernapas lepas, sebab ternyata, si pemulunglah yang mereka sasar.
Dengan sigap, polisi-polisi itu kemudian memeriksa sekujur tubuh si pemulung, seperti mencari benda atau barang-barang terlarang. Tetapi mereka seperti tak menemukan apa-apa. Meski begitu, mereka tetap memborgol si pemulung, lalu membawanya dengan tudingan yang serius.
Aku sungguh tak menyangka bahwa si pemulung yang tampak polos dan baik itu akan berurusan dengan perkara hukum yang pelik.
Setelah peristiwa penangkapan itu terjadi, aku pun mengembuskan napas yang panjang. Aku benar-benar merasa lega, sebab meski si pemulung digelandang dengan sangkaan sebagai pengedar narkotika, para polisi sama sekali tidak mengendus perihal perkaraku di masa lalu.
Sesaat kemudian, aku kembali ke teras rumahku, lalu duduk di kursi dudukanku sebelumnya. Dan seketika, mataku tertuju ke sisi bawah kursi bekas tempat duduk si pemulung. Di situ, aku melihat tas kecil yang jelas bukan punyaku.
Dengan rasa penasaran, aku lalu membawanya ke dalam kamarku, lantas membukanya. Hingga akhirnya, aku melihat butiran kristal sabu-sabu di dalam plastik-plastik yang berukuran kecil.
Perasaan dan pikiranku pun berkecamuk.*
*Penulis : Ramli Lahaping. Kelahiran Gandang Batu, Kabupaten Luwu. Berdomisili di Kota Makassar. Instagram (@ramlilahaping) Facebook (Ramli Lahaping).



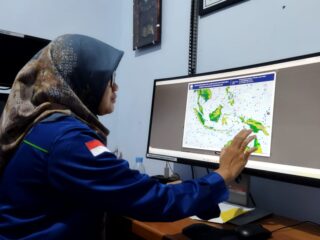














No Comments