
Dari Mimbar Jalanan ke Perang Linimasa: Peta Baru Gerakan Mahasiswa di Era Digital Indonesia

Oleh : Afdal Salputra Program Studi Hukum Keluarga
(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)
Bayangkan sejenak tahun 1998. Gambaran ikonik seorang aktivis mahasiswa adalah sosok yang berdiri di atap mobil komando, berorasi dengan pengeras suara, di tengah lautan manusia yang memadati jalanan ibu kota. Spanduk terbentang, pamflet disebar dari tangan ke tangan. Kekuatan mereka diukur dari seberapa banyak massa yang berhasil dikumpulkan dan seberapa lama mereka mampu menduduki ruang-ruang simbolik kekuasaan.
Sekarang, lompat ke hari ini. Gambaran itu bergeser drastis. Seorang aktivis mungkin sedang duduk di kamar kosnya, berbekal laptop dan koneksi internet. Dengan beberapa ketukan jari, ia merangkai utas (thread) di X (dulu Twitter) yang membedah kebijakan kontroversial, mendesain poster digital yang provokatif untuk Instagram, atau mengoordinasikan aksi melalui grup WhatsApp. Dalam hitungan jam, pesannya bisa menjangkau jutaan orang, memicu gelombang kemarahan dari Sabang sampai Merauke.
Medan perang telah bergeser. Dari mimbar jalanan ke linimasa media sosial. Ini adalah peta baru gerakan mahasiswa Indonesia di era masyarakat digital, sebuah arena yang mengubah total cara mereka berjuang, tantangan yang dihadapi, dan bahkan arti dari aktivisme itu sendiri.
Warisan Jalanan: Modal Politik Bernama “Kekuatan Moral”
Untuk memahami skala perubahan ini, kita perlu menengok kembali ke fondasi gerakan mahasiswa modern. Jauh sebelum 1998, mahasiswa telah menjadi motor perubahan. Dari lahirnya Budi Utomo pada 1908 oleh mahasiswa STOVIA, Sumpah Pemuda 1928 yang dimotori para pelajar terdidik, hingga Angkatan ’66 yang menyuarakan Tritura dan menjadi kekuatan kunci transisi ke Orde Baru. Sejarah panjang ini mengukuhkan identitas mahasiswa sebagai “kekuatan moral” (moral force) suara hati nurani bangsa yang bergerak atas dasar idealisme.
Puncak dari aktivisme berbasis kekuatan fisik ini adalah Reformasi 1998. Dipicu oleh krisis ekonomi dan politik yang melumpuhkan negeri, mahasiswa tampil sebagai agen perubahan (agent of change) yang menumbangkan rezim Orde Baru. Senjata utama mereka adalah penguasaan ruang fisik. Aksi-aksi masif seperti long march dan, yang paling menentukan, pendudukan Gedung DPR/MPR menjadi strategi kunci yang melumpuhkan legitimasi penguasa. Kehadiran fisik ribuan mahasiswa di pusat kekuasaan mengirimkan pesan yang tak terbantahkan: rakyat tidak lagi percaya. Warisan inilah yang menjadi modal politik bagi generasi aktivis hari ini. Ketika mereka bergerak, mereka tidak memulai dari nol; mereka meminjam legitimasi historis yang telah dibangun oleh para pendahulunya.
Alun-Alun Baru Bernama Media Sosial
Memasuki abad ke-21, alun-alun tempat publik berkumpul telah berpindah. Linimasa media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok kini menjadi ruang publik virtual utama tempat opini dibentuk dan narasi politik diperjuangkan. Bagi gerakan mahasiswa, ini adalah sebuah revolusi. Platform digital menawarkan “senjata” baru yang sangat ampuh:
Tagar sebagai Seruan Perang: Tagar seperti #GejayanMemanggil atau #ReformasiDikorupsi bukan sekadar penanda. Ia adalah simbol pemersatu, kerangka isu, dan alat koordinasi yang mampu mengubah masalah lokal menjadi perhatian nasional dalam sekejap.
Akselerasi Informasi: Seruan aksi dan materi edukasi kini dapat disebar dengan kecepatan kilat ke jutaan orang, melampaui batas geografis dengan biaya minimal.
Petisi Daring sebagai Alat Tekan: Platform seperti Change.org memungkinkan gerakan menunjukkan dukungan publik secara kuantitatif. Jutaan tanda tangan digital menjadi bukti nyata adanya keresahan massa yang sulit diabaikan.
Struktur gerakan pun berubah. Jika dulu cenderung hierarkis, gerakan digital kini lebih cair, terdesentralisasi, dan seringkali tanpa pemimpin tunggal. Namun, di balik kekuatannya, ada paradoks. Kemudahan berpartisipasi melahirkan fenomena “aktivisme sofa” atau slacktivism keterlibatan semu sebatas like, share, atau tanda tangan petisi tanpa komitmen lebih lanjut. Ini bisa menciptakan ilusi dukungan massa yang rapuh. Selain itu, muncul adagium “No Viral, No Action,” di mana sebuah isu dianggap tidak akan mendapat respons jika tidak meledak di media sosial, sebuah ketergantungan yang berisiko mengorbankan substansi demi daya tarik algoritma.
#ReformasiDikorupsi & #TolakOmnibusLaw: Lahirnya Aktivisme Hibrida
Dua gerakan besar pasca-1998, #ReformasiDikorupsi (2019) dan #TolakOmnibusLaw (2020), menjadi contoh sempurna bagaimana model aktivisme baru ini bekerja. Keduanya bukan murni gerakan daring atau luring, melainkan sebuah aktivisme hibrida yang efektif.
Pada September 2019, gelombang protes #ReformasiDikorupsi meletus sebagai respons atas pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pembahasan RKUHP yang dinilai antidemokrasi. Kampanye digital yang masif di media sosial dengan tagar seperti #ReformasiDikorupsi dan #GejayanMemanggil berhasil membingkai isu ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat Reformasi. Hasilnya luar biasa: kemarahan daring tumpah ke jalanan. Puluhan ribu mahasiswa di berbagai kota turun serentak, menjadikannya demonstrasi terbesar sejak 1998. Namun, gerakan ini memakan korban. Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Randi dan Yusuf Kardawi, tewas tertembak saat aksi, menjadi martir yang semakin menyulut kemarahan publik.
Setahun kemudian, pola yang sama terulang dalam gerakan #TolakOmnibusLaw. Pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial memicu perlawanan sengit. Selain perang tagar seperti #MosiTidakPercaya, sebuah petisi daring di Change.org berhasil mengumpulkan lebih dari 1,2 juta tanda tangan. Energi digital ini kembali dikonversi menjadi aksi mogok nasional dan demonstrasi besar-besaran yang melumpuhkan sejumlah kota.
Kedua kasus ini menunjukkan sebuah siklus strategis: momentum daring digunakan untuk memicu aksi fisik, dan dokumentasi aksi fisik (terutama gambar atau video kebrutalan aparat) disebar kembali ke dunia maya, menciptakan gelombang kemarahan baru yang lebih besar. Inilah inti dari aktivisme hibrida: perpaduan antara jangkauan global dunia maya dengan tekanan nyata dari kehadiran fisik di dunia nyata.
Perang Tak Terlihat: Sisi Gelap Aktivisme Digital
Namun, arena digital adalah pedang bermata dua. Di balik kekuatannya, tersimpan risiko dan ancaman yang tak kalah besar. Para aktivis kini berada dalam medan perang asimetris.
Pertama, represi digital oleh negara. Pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap digunakan sebagai alat hukum untuk membungkam suara-suara kritis dan mengkriminalisasi aktivis. Patroli siber oleh aparat secara aktif memantau aktivitas online, dan peretasan akun aktivis sering terjadi menjelang aksi besar untuk melumpuhkan koordinasi.
Kedua, serangan “pasukan siber” atau buzzer politik. Mereka adalah aktor bayaran yang bekerja secara terorganisir untuk mengacaukan narasi, menyebarkan disinformasi, dan melancarkan serangan personal yang brutal. Taktik mereka meliputi pembajakan tagar (hashtag hijacking) untuk menenggelamkan pesan gerakan dan menciptakan “suara bising” yang membuat diskusi substantif menjadi mustahil.
Ketiga, teror doxing. Ini adalah bentuk serangan paling kejam, di mana data pribadi seorang aktivis (alamat rumah, nomor telepon, data keluarga) disebar ke publik. Ancaman yang tadinya virtual kini berpindah ke depan pintu rumah mereka, menciptakan teror psikologis yang nyata dan mendalam bagi korban dan keluarganya.
Terakhir, kesehatan mental para aktivis menjadi taruhan. Menjadi target konstan dari perundungan siber, ujaran kebencian, dan ancaman memberikan beban psikologis yang luar biasa berat, yang dapat berujung pada kecemasan, depresi, hingga kelelahan ekstrem (burnout).
Merajut Masa Depan: Menuju Ekosistem Perlawanan
Wajah gerakan mahasiswa Indonesia telah berubah selamanya. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan warisan moral dan kekuatan jalanan. Di sisi lain, sekadar viral di dunia maya pun terbukti tidak cukup untuk mengubah kebijakan.
Masa depan aktivisme yang efektif terletak pada konvergensi strategis: kemampuan untuk memadukan disiplin pengorganisasian di dunia nyata dengan kelincahan perang narasi di dunia maya. Ini menuntut lahirnya generasi aktivis yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdas dan tangguh secara digital (digital resilience).
Perlawanan kini tidak lagi bersifat individual atau sporadis, melainkan mulai terwujud dalam sebuah ekosistem perlawanan. Mahasiswa sebagai motor penggerak massa kini ditopang oleh berbagai elemen masyarakat sipil dengan keahlian spesifik:
Keamanan Digital: Organisasi seperti SAFEnet menyediakan pelatihan bagi para aktivis untuk melindungi diri dari peretasan dan pengawasan.
Perang Melawan Hoaks: Inisiatif kolaboratif seperti CekFakta.com, yang digagas oleh AJI, Mafindo, dan AMSI, bekerja untuk memverifikasi informasi dan melawan disinformasi secara sistematis.
Advokasi Hukum: Lembaga bantuan hukum seperti YLBHI dan LBH Pers berada di garis depan, melawan upaya kriminalisasi terhadap aktivis melalui jalur litigasi dan advokasi reformasi UU ITE.
Gerakan mahasiswa di era digital bukan lagi entitas tunggal, melainkan simpul penting dalam sebuah jejaring perlawanan yang lebih luas. Keberhasilan mereka di masa depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras mereka berteriak di jalanan atau seberapa viral tagar mereka, tetapi oleh seberapa kuat, terintegrasi, dan adaptifnya keseluruhan ekosistem ini dalam menghadapi medan perang yang terus berubah. Inilah wajah baru perjuangan untuk menjaga denyut demokrasi di Indonesia.





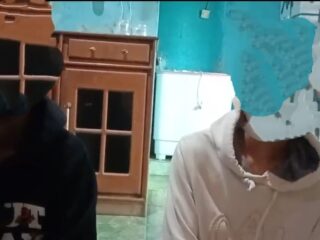











No Comments